Zoreen Muhammad
Insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal keamanan pangan. Di balik itu, tersimpan kisah anak-anak yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit, orang tua yang panik, guru-guru yang merasa bersalah, dan publik yang bertanya-tanya: siapa yang harus bertanggung jawab, dan seperti apa bentuk keadilannya?
Sayangnya, dalam banyak peristiwa serupa, maaf saja sering kali tak cukup. Ketika tubuh anak-anak telah terpapar bakteri, ketika muntah dan pingsan menjadi pengalaman yang membekas di kepala mereka, negara ditantang untuk hadir secara konkret, bukan hanya lewat pernyataan pers. Salah satu bentuk kehadiran itu adalah melalui skema kompensasi yang adil. Dan untuk merumuskannya, kita tak perlu mulai dari nol. Dunia sudah lebih dulu menghadapi situasi serupa—dan dari sanalah kita bisa belajar.
Mari mulai dari Jepang. Kasus Minamata jadi salah satu tragedi keracunan makanan paling ikonik dalam sejarah modern. Di kota kecil itu, perusahaan bernama Chisso Corp membuang limbah mengandung merkuri ke teluk, yang kemudian masuk rantai makanan melalui ikan. Warga yang mengonsumsi ikan tersebut perlahan menunjukkan gejala aneh—kejang, kerusakan syaraf, dan kematian. Butuh waktu bertahun-tahun bagi korban untuk diakui secara hukum. Namun pada akhirnya, pengadilan memerintahkan pemerintah dan perusahaan membayar kompensasi sekitar 2,75 juta yen untuk setiap korban yang diakui secara medis. Totalnya, ratusan juta dolar dikeluarkan dalam berbagai bentuk: perawatan medis, santunan, hingga pembangunan rumah sakit khusus.
Apa pelajaran dari Minamata? Pertama, negara dan korporasi tak bisa lepas tangan. Kedua, kompensasi bukan sekadar transfer uang, tapi juga bentuk pengakuan atas luka yang telah terjadi. Pengakuan inilah yang membuat korban merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar statistik dalam laporan insiden.
Kita beralih ke India, ke kota Bhopal, tahun 1984. Kebocoran gas dari pabrik pestisida milik Union Carbide menyapu malam dengan gas beracun. Dalam hitungan jam, ribuan orang tewas. Ratusan ribu lainnya menderita penyakit seumur hidup. Di tengah kekacauan, perusahaan kabur, pemerintah bungkam. Butuh waktu lima tahun hingga kompensasi formal diberikan: US$470 juta untuk seluruh korban. Jumlah yang sangat besar, tapi tetap dirasa tak memadai. Banyak korban tak pernah menerima sepeser pun. Prosedurnya kacau, distribusinya tidak transparan, dan lagi-lagi yang lemah tak punya suara.
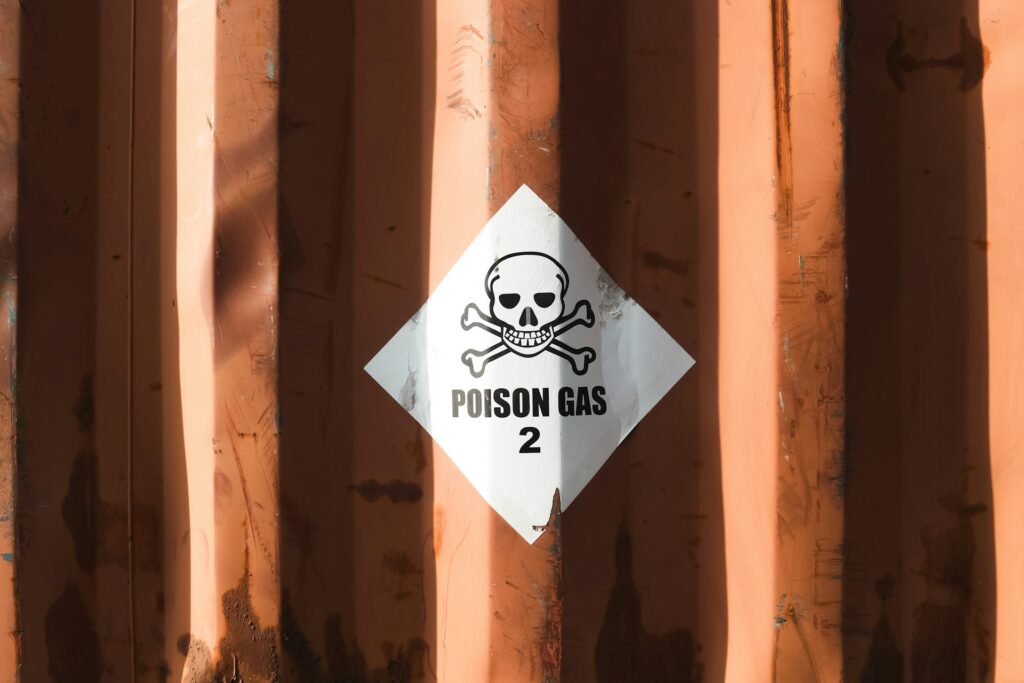
Kasus Bhopal memberi pelajaran penting soal transparansi. Kompensasi hanya berarti jika sistem distribusinya bisa dipercaya. Ketika negara terlalu birokratis, korban bisa jadi korban dua kali—pertama karena insiden, kedua karena tidak mampu mengakses haknya.
Lalu ada Corby di Inggris. Kota ini pernah menjadi pusat industri baja, tapi juga lokasi pembuangan limbah berbahaya. Proyek reklamasi yang dimaksudkan untuk revitalisasi malah menyebabkan anak-anak lahir cacat akibat paparan zat beracun. Setelah proses hukum selama sebelas tahun, pengadilan memutuskan bahwa dewan kota Corby bersalah dan harus membayar kompensasi kepada keluarga korban. Kasus ini istimewa, karena yang digugat adalah pemerintah lokal, bukan perusahaan. Artinya, akuntabilitas publik juga diuji di sini.
Corby menunjukkan bahwa bahkan tanpa niat jahat, kelalaian pemerintah tetap bisa berujung pada penderitaan warganya. Dan itu layak dikompensasi. Tak perlu menunggu demonstrasi atau tekanan politik. Cukup hati nurani dan sistem hukum yang berfungsi.
Nah, kembali ke Indonesia. Kasus keracunan MBG memang belum sebesar Minamata, Bhopal, atau Corby. Tapi bukan berarti kita harus menunggu semuanya memburuk baru bertindak. Justru sekaranglah saatnya merumuskan pendekatan kompensasi yang adil, manusiawi, dan sesuai konteks. Kemurahan hati kepala Badan BGN Dadan Hindayana yang merogoh koceknya sendiri sebagai kompensasi kita pandang sebagai solusi humanis beliau, tapi kita butuh pendekatan sistemik bila hal-hal demikian terjadi kembali.
Beberapa usulan sudah mulai muncul. Misalnya, gagasan membentuk dana kompensasi yang dikelola lembaga independen. Dana ini akan digunakan untuk menanggung biaya pengobatan, memberikan santunan, dan jika perlu, membiayai pemantauan kesehatan jangka panjang. Ini penting karena efek keracunan makanan tidak selalu langsung terlihat. Beberapa bisa memicu masalah usus kronis atau alergi berkepanjangan.
Pakar-pakar kesehatan seperti Dr. Ingrid Eckerman dari Swedia yang pernah meneliti Bhopal menekankan pentingnya deteksi dini dan pemantauan jangka panjang. Sementara Human Rights Watch menyoroti bahwa dalam banyak kasus, korban tak hanya butuh uang, tapi juga perlakuan manusiawi dan proses yang adil. Mereka bahkan pernah mendesak PBB untuk membayar kompensasi atas keracunan timbal di kamp pengungsi di Kosovo, sebagai bentuk tanggung jawab institusional.
Bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki sejumlah instrumen hukum seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, hingga Peraturan Presiden tentang tanggap darurat kesehatan masyarakat. Namun semua ini baru akan berarti jika diterapkan secara konsisten. Misalnya, dalam kasus keracunan MBG, apakah pemerintah bersedia mengakui bahwa ini adalah kegagalan sistemik? Apakah instansi terkait mau terbuka menyebut asal bahan makanan yang terkontaminasi? Apakah vendor-vendor penyedia bahan baku akan dimintai pertanggungjawaban?
Lalu soal bentuk kompensasinya, mungkinkah pemerintah memberi tiga bentuk sekaligus: finansial, medis, dan simbolik? Finansial, tentu untuk biaya langsung seperti pengobatan dan transportasi. Medis, untuk akses rawat lanjutan dan rehabilitasi. Dan simbolik, seperti pernyataan maaf resmi, pembangunan fasilitas kesehatan baru, atau beasiswa bagi anak-anak terdampak.
Di Amerika Serikat, korban keracunan makanan akibat kelalaian restoran atau pabrik bisa menggugat hingga jutaan dolar. Tapi prosesnya didukung sistem hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat tinggi. Di Jepang dan Eropa, ada mekanisme asuransi sosial dan lembaga ombudsman yang siap turun tangan. Indonesia mungkin belum sampai di sana, tapi bukan berarti tak bisa belajar.
Yang perlu dihindari adalah skenario saling lempar tanggung jawab. Ketika kementerian saling menyalahkan, ketika vendor merasa tak tersentuh, ketika sekolah merasa dijebak keadaan, dan ketika masyarakat kebingungan harus lapor ke siapa—saat itulah negara tampak tak hadir. Sebaliknya, ketika korban segera ditangani, data diverifikasi, bantuan diberikan, dan pemerintah secara terbuka menjelaskan langkah yang diambil, di situlah kepercayaan publik mulai pulih.
Apalagi program MBG ini bukan proyek kecil. Ini adalah janji politik dan kebijakan besar yang menyangkut jutaan anak Indonesia. Jika gagal di tahap awal karena soal keracunan yang tak ditangani serius, maka ke depannya program ini akan kehilangan legitimasi. Dan itu bisa sangat merugikan, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga generasi masa depan.
Sudah saatnya kita bicara soal kompensasi bukan sebagai bentuk belas kasihan, tapi sebagai hak. Korban bukan pengemis bantuan, mereka adalah warga negara yang dirugikan oleh miss dalam sistem belum sempurna dan sedang berupaya disempurnakan oleh BGN. Negara bukan sekadar pembuat program, tapi penjamin kualitas dan keselamatan pelaksanaannya.
Kalau Jepang bisa menuntut Chisso, India bisa mengadili Union Carbide, dan Inggris bisa membuat dewan kotanya bertanggung jawab, mengapa Indonesia tidak bisa menjadikan MBG lebih bertanggung jawab pula?
Langkah pertama bisa dimulai dengan mengakui korban. Bukan hanya sebagai nama dalam daftar, tapi sebagai manusia yang perlu dihormati. Lalu membentuk tim lintas kementerian untuk menyusun standar kompensasi. Melibatkan BGN, BPOM, Kemenkes, serta lembaga perlindungan anak. Tak lupa, menyertakan organisasi masyarakat sipil agar proses ini tak jadi urusan elit saja.
Dan bila perlu, revisi aturan yang belum memungkinkan pemberian kompensasi dalam situasi non-bencana. Karena keracunan massal di sekolah, meskipun tak separah gempa atau tsunami, tetaplah bencana bagi keluarga korban.
Tentu, semua ini butuh kemauan politik, keberanian moral, dan koordinasi yang rapi. Tapi bukan mustahil. Karena di balik setiap insiden keracunan, ada satu hal yang lebih penting dari anggaran atau regulasi: martabat manusia. Dan kompensasi, ketika dilakukan dengan benar, bukan hanya mengganti yang hilang—tapi mengembalikan harapan.

